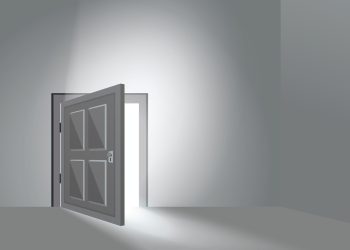Oleh: Muhamad Mahfud Muzadi
Tawadlu; humble; rendah hati; andap asor; merupakan salah satu akhlaq terpuji yang sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap manusia. Telah banyak dalil yang menerangkan tentang perintah tawadlu, baik yang disebutkan dalam al-Quran maupun Hadits. Namun pada kenyataannya akhlak ini susah untuk diamalkan karena harus melawan sifat sifat tercela yang dekat dengan kita, seperti takabbur, riya, sumah, bahkan ujub. Karena sejatinya penyakit-penyakit ini lebih berbahaya dan lebih susah disembuhkan dibanding dengan Covid-19 yang sedang viral ini.
Covid-19 baru muncul akhir 2019 dan insya Allah akan segera berakhir dan ditemukan vaksinnya. Akan tetapi sifat takabur dan saudara-saudaranya itu telah ada sejak Nabi Adam AS diciptakan yaitu dilakukan pertama kali oleh iblis yang tidak mau bersujud kepada nabi adam karena merasa dirinya lebih mulia. Inilah perbuatan takabur pertama yang dilakukan oleh seorang makhluk.
Sekarang ini, bahkan lebih ngeri lagi, sifat tawadu yang mulia ini dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar semakin dipuji oleh orang lain. Terjadi kesalahan implementasi dari tawadlu ini yang sering dikenal dengan merendah untuk meroket. Yaitu merendah dengan sengaja agar lebih dipuji-puji orang lain. Naudzubuliilah
Lantas bagaimanakah hakikat tawadlu yang sebenarnya? Ada dua kisah tentang tawadhu’ yang sangat menakjubkan yang dilakukan oleh Wali Allah yang bisa kita jadikan sebagai teladan dalam memahami hakikat tawadlu
Pertama adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Syaikh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi dalam kajian Hikam-nya:
Salah satu orang sholih tengah berthawaf kala itu, kemudian ia melihat seseorang bersujud sambil menangis sesenggukan. Setelah ia dekati, ternyata orang tersebut adalah Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, sosok ulama besar yang dijuluki sebagai Sulthonul awliya’ (Sultan para wali). Kala itu Dalam tangis dan sujud panjangnya, Syaikh Abdul Qadir berdoa: “Ya Allah. jika engkau memang tidak ingin mengampuni dosa-dosaku kelak di hari kiamat maka bangkitkanlah diriku kelak dalam keadaan buta. Sehingga aku tidak malu kepada orang-orang yang dulu berbaik sangka kepadaku”
Sungguh doa beliau ini merupakan contoh akhlak yang sangat terpuji. Beliau selalu menganggap dirinya seorang pendosa meski sebagaimana yang kita ketahui beliau merupakan pemimpin atau raja dari para kekasih Allah.
Kisah kedua adalah kisah yang dituliskan oleh Syaikh Ibnu Ajibah al-Hasani dalam Syarah Hikam-nya:
Suatu hari di musim hujan Syaikh Abdurrahman Bin Said yang merupakan seorang ulama besar sedang melewati jalanan yang becek dan berlumpur. Tiba-tiba tampak seekor anjing datang dari arah yang berlawanan. Melihat anjing itu semakin mendekat, beliau menepi ke tempat yang bersih dan tak berlumpur agar anjing itu melewati jalan yang berlumpur. Akan tetapi tak lama kemudian beliau justru berpindah ke tempat yang berlumpur lagi seakan mempersilahkan anjing tersebut untuk berjalan melalui tempat bersih yang tadi sempat ditempatinya.
Saksi mata yang melihat kejadian “aneh” tersebut segera mendatangi Syaikh Abdurrahman. Ketika itu di atas kubangan lumpur beliau tampak sedih dan termenung.
“Wahai Syaikh. barusan aku melihat engkau melakukan hal yang sangat aneh. Mengapa engkau mengalah dan membiarkan anjing itu lewat melalui jalan yang bersih dan tak berlumpur?”
“Awalnya aku memang ingin membiarkan anjing itu lewat melalui jalan yang kotor, namun kemudian aku berfikir dan berkata dalam hati: “bukankah anjing itu lebih baik dan lebih mulia dari diriku? Aku punya banyak dosa dan masih sering bermaksiat sedangkan anjing itu tidak mempunyai dosa sama sekali? Kalau begitu bukankah ia lebih pantas dimuliakan daripada diriku yang hina ini? Sekarang aku sedih dan takut Allah tidak akan mengampuni dosaku karena aku telah merendahkan salah satu mahluk-Nya yang lebih mulia dariku”
Masya Allah. Akhlak seperti ini yang di pegang teguh oleh para kekasih Allah sehingga budi pekerti mereka selalu indah dan luhur. Ibarat padi yang semakin tinggi semakin merunduk, semakin berisi semakin merendah. Merekalah teladan dari hakikat tawadlu yang sebenarnya.
Lalu kita yang manusia biasa dengan segala kesalahan dan kekhilafannya, masih pantaskah kita menyombongkan diri? Jika memang meneladani para Wali Allah masih dirasa sangat berat, setidaknya kita tidak terlalu jauh melenceng dari akhlak-akhlak mulia mereka.
Terakhir, jika ada pertanyaan kapan seseorang bisa dikatakan orang yang tawadlu? Yaitu: “ketika ia tidak melihat kebaikan atau keistimewaan apapun dalam dirinya, dan selalu meyakini bahwa di bumi ini tidak ada orang yang lebih hina dari dirinya” – Abu Yazid al-Bustomi.
Wallahu A’lam…
Penulis merupakan salah satu mahasantri Pesantren Rist Al-Muhtada dan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang