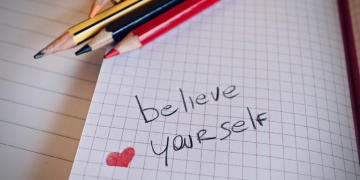almuhtada.org – Mungkin di telinga kita sudah tidak asing dengan kata “makelar”, yaitu sebutan untuk orang yang menjadi perantara atau calo, yang biasanya ikut campur di belakang layar untuk mengatur hasil suatu urusan demi keuntungan pribadi.
Istilah ini kembali mencuat ke publik setelah adanya kasus yang menghebohkan jagat media sosial dengan temuan uang senilai Rp915 miliar dan emas seberat 51 kilogram di rumah Zarof Ricar, eks pejabat Mahkamah Agung, saat dilakukan penyidikan.
Zarof Ricar sendiri diduga sebagai makelar dalam kasus Ronald Tannur, yang sempat dijatuhi vonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya.
Ronald Tannur sendiri merupakan anak eks anggota DPR RI Fraksi PKB, Edward Tannur, terdakwa pembunuhan sadis atas kekasihnya yakni Dini Sera Afrianti (29). Dalam kasus ini, pelaku yakni Ronald Tannur divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya.
Tentunya hal ini menjadi tanda tanya besar bagi publik: bagaimana mungkin pengadilan memvonis Ronald Tannur bebas, padahal jaksa sebelumnya menuntut Ronald Tannur untuk dihukum 12 tahun penjara dan membayar restitusi atau ganti kerugian pada keluarga korban senilai Rp263,6 juta?
Kasus ini tentunya membuat masyarakat awam bertanya-tanya: apa itu sebenarnya Mahkamah Agung? Apa kewenangannya? Serta bagaimana jika di dalamnya terdapat makelar?
Apabila kita melihat kewenangan Mahkamah Agung, hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:
“Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Sedangkan kewenangan Mahkamah Agung sendiri terdapat dalam Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi:
“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”
Sehingga apabila kita lihat bersama, bahwasanya apabila suatu kasus atau perkara diputus oleh pengadilan, maka seorang tergugat atau penggugat yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut, atau terdapat kesalahan dalam pertimbangan fakta serta penerapan hukum yang tidak tepat, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
Namun apabila setelah putusan banding dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi, para pihak masih merasa tidak puas terhadap hasil putusan tersebut karena terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, pelanggaran hukum acara, atau putusan tidak memenuhi syarat formal, maka dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.
Dalam proses kasasi ini, Mahkamah Agung tidak lagi menilai ulang fakta suatu perkara, melainkan hanya menilai apakah hukum yang telah diterapkan terhadap perkara tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum.
Sehingga dari sini dapat kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan final di Indonesia. Namun, apa jadinya jika pengadilan tertinggi setinggi Mahkamah Agung yang menjadi benteng akhir dari suatu keadilan justru ternodai oleh praktik makelar kasus?
Yang terjadi adalah kerusakan pada suatu lembaga dan juga retaknya seluruh fondasi kepercayaan publik terhadap sistem hukum di negeri ini.
Selain dampak tersebut, juga dampak yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Ketika benteng terakhir keadilan justru menjadi tempat di mana keadilan bisa diperjualbelikan, maka harapan rakyat untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum akan lenyap, digantikan oleh rasa curiga, kecewa, bahkan putus asa.
Mahkamah Agung yang seharusnya menjadi simbol ketegasan dan kejujuran dalam menegakkan hukum, malah justru menjadi tempat untuk “menawar putusan”. Selain itu, tentunya masyarakat kelas kecil atau miskin cenderung akan terpinggirkan dan tersingkir.
Sehingga dengan adanya praktik makelar ini, hukum hanya akan berpihak kepada para pemilik uang. Hal ini tentu tidak sejalan dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” serta pembukaan Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”
Padahal, jika kita melihat kembali, ruh dasar dari hukum adalah:
“Salus populi suprema lex esto” (Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi)
Maka jika hukum tidak lagi berpihak pada rakyat, melainkan pada kepentingan dan uang, artinya kita telah menjauh dari cita-cita hukum itu sendiri. Dan ketika keadilan hanya menjadi milik segelintir orang, maka negara hukum hanyalah sebuah ilusi.
[Juliana Setefani Usaini]