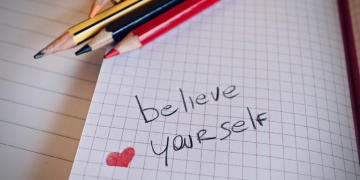Oleh Dwi Wisnu Kurniawan
Istilah Masyarakat sadar hukum terdiri atas 3 kata, yakni masyarakat, sadar dan hukum. Kata “masyarakat” merujuk pada kondisi sekelompok orang yang hidup secara bersama-sama dalam lingkungan sosial untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kata “sadar” berarti mengetahui, atau memahami dengan seluruh keyakinan yang dimiliki bahwa apa yang diketahui dan dilakukan dalam berbuat membawa dampak langsung dan tidak langsung terhadap diri dan sekitarnya. Selanjutnya kata “hukum” berkaitan dengan kaidah, pedoman, tuntunan, aturan tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat memaksa / imperative dan mengikat secara umum bagi setiap orang dalam pergaulan hidup sosial.
Sehingga, dapat ditarik pengertian dari masyarakat sadar hukum adalah sekelompok orang yang hidup pada suatu tempat secara bersama-sama dalam upaya mewujudkan tujuan bersama dengan bekal pemahaman yang dimiliki melaksanakan segala kaidah-kaidah yang berlaku ditengah lingkungan sosial untuk dihormati dan dilakukan secara rasional.
Kesadaran akan hukum menjadi penyangga dalam kehidupan bernegara, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945), yang mengukuhkan bahwa keberadaan hukum sebagai panglima dalam otoritas mengatur tata pemerintahan dan kehidupan bernegara. Hal ini menegaskan bahwa negara Indonesia bukan negara kekuasaaan (machtsstaat) yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah.
Negara hukum Indonesia sebagaimana konsepsi yang terbangun sebagai suatu negara hukum memiliki perbedaan dengan konsep rechtstaat atau rule of law, Philipus Hadjon berpendapat bahwa negara hukum yang dibangun Indonesia adalah negara hukum berdasarkan atas Pancasila yang dalam implementasinya menghendaki kesesuaian antara Pemerintah dengan rakyat dengan mengutamakan asas kerukunan (Wiyono, 2016, p. 2).
Maka prinsip-prinsip yang dibangun pada negara hukum Indonesia tidak saja melihat pada hukum dalam mengelola soal kedudukan, kewenangan, badan-badan pemerintahan dan sengketa antara rakyat dengen pemerintah, namun lebih jauh dari itu bahwa operasionalisasi hukum menyentuh pada hubungan antara negara dan rakyatnya atas dasar hubungan proporsionalitas antara kewajiban dan hak dalam menjalankan kewenangan negara dan rakyatnya, merumuskan suatu kebijakan dan menyelesaikan persoalan melalui jalan musyawarah-mufakat, serta jalinan hubungan substantif berupa pondasi kesadaran untuk menerapkan hukum berasal dari internal masyarakat.
Menurut Ewick dan Silbey melihat bahwa kesadaran hukum merupakan pemahaman akan substansi yang terkandung dalam hukum diproyeksikan melalui pengalaman dan tindakan orang. Dalam kesadaran hukum berada pada ranah hukum dalam tindakan manusia, bukan pada hukum yang mengandung muatan atas norma dan asas (Kenedi, 2015, p. 206).
Kesadaran hukum sebagaimana pendapat L.Pospisil bertalian dengan ketaatan masyarakat yang terdiri atas 3 jenis (Kenedi, 2015, p. 208), yakni:
- Ketaatan yang bersifat compliance, maksudnya ketaatan terhadap hukum dikarenakan takut akan sanksi yang akan diterima oleh pelaku nantinya, kelemahan pada jenis ini dalam implementasi dilapangan membutuhkan unsure pengawasan untuk menerapkan ketaatan terhadap hukum yang sedang berjalan;
- Ketaatan bersifat identification, maksudnya ketaatan terhadap hukum disebabkan karena takut akan merusak hubungan dengan pihak lain;
- Ketaatan bersifat internalization, maksudnya ketaatan terhadap hukum diperoleh melalui proses internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam aturan dan sesuai dengan nilai yang diyakininya. Ketaataan berdasarkan proses internalisasi nilai-nilai atas keyakinan memiliki dimensi yang baik dalam melaksanakan aturan hukum yang berjalan. Orang yang sadar akan keberadaan aturan dan makna dibaliknya akan berjalan mengikuti garis hukum yang telah ditetapkan dengan penuh pertimbangan rasio akal sehat dan tindakan.
Suko Wiyono berpendapat bahwa dalam pembangunan hukum secara makro kaitannya dengan teori dari Pogorecki memberikan pendekatan yang seharusnya dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum melalui momen pembentukan undang-undang dengan 4 model, yakni momen ideal-filosofis, momen politik-partisipatif, momen normatif dan momen teknis-yuridis.
Keempat model yang ada memiliki taraf dan dimensi yang berlainan satu dengan lainnya, momen ideal-filosofis memberikan pendekatan bahwa penumbuhan kesadaran hukum melalui pandangan filosofis melalui pandangan hidup, ideologi, sejarah dan kesadaran hukum akan nilai-nilai yang masyarakat anut sebagai basis landasan filosofis dalam ketentuan hukum. Materi dalam momen ideal-filosofis harus menancap kuat pada setiap bait kata ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalam momen ideal-filosofis dengan pendekatan secara top down, isi dalam ketentuan hukum dapat diterima sebagai suatu ketentuan yang membawa kepastian, keadilan dan kemanfaatan (Wiyono, 2016, p. 6).
Sedangkan momen politik-partisipatif dengan pendekatan buttom up adalah substansi sosial dalam penyerapan aspirasi politik yang dilakukan oleh para legislator dalam mengagregasi atas apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk dituangkan dalam kebijakan riil. Kemudian momen normatif merupakan landasan yuridis berlakunya aturan perundang-undangan ditengah masyarakat. Momen normatif berkolerasi dengan momen teknis-yuridis yang keduanya berada dalam area sentral dalam pembentukan hukum melalui serangkaian aktivitas legal drafting dalam mengelola bahan baku perundangan berupa momen ideal-filosofis dan partisipatif-politik masyarakat pada setiap ketentuan pasal yang tersusun dalam rancangan undang-undang. Pada momen teknis-yuridis para ahli hukum dalam merancang undang-undang harus meramu sistematika, asas-asas, muatan, dan sarana prasarana yang diterapkan (Wiyono, 2016, p. 8).
Kesadaran hukum bukan hanya sebatas pengetahuan akan aturan hukum dan dapat melafalkannya dengan lancar. Namun, kesadaran hukum menuntut kondisi jiwa dan pikiran manusia yang mampu memahami dengan sepenuhnya bahwa keyakinan terhadap keberlakuan kaidah hukum tertentu akan membawa dampak bagi dirinya dan lingkungan sosial.
Kesadaran mengenai keberlakuan norma hukum dan latarbelakang dibelakangnya, selanjutnya dilakukan proses internalisasi yang rumit dan kompleks dalam diri manusia sampai menanamkan dalam pikiran dan bathin bahwa pemahaman akan kaidah hukum yang dijadikan penuntun dalam melakukan berbagai perbuatan yang terbawa dalam tindakan-tindakan alamiah guna merespon dinamika sosial yang berkembang.
Pembangunan atas kesadaran hukum masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah, sebab dalam dinamika kehidupan masyarakat yang kompleks tidak sulit dijumpai adanya pelanggaran, bentrokan atau conflict of interest. Menurut Soerjono Soekanto kesulitan pembangunan kesadaran hukum karena pejabat yang bertanggung jawab tidak mengetahui mengenai kewajiban yang mesti diembannya dan kurang kepekaan akan fungsi pembangunan (Kenedi, 2015, p. 107).
Faktor lain yang menjadi pemicu dari kurang sadar terhadap hukum (Kenedi, 2015, p. 207) yakni;
- adanya ketidakpastian mengenai ketentuan hukum yang berlaku;
- peraturan yang berlaku sifatnya statis;
- cara mempertahankan hukum yang berlaku oleh masyarakat tidak efisien.
Kemudian, faktor-faktor yang membuat masyarakat kurang sadar akan hukum atau kurang taat hukum oleh Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor (Kenedi, 2015, p. 210)sebagai berikut:
- faktor hukum sendiri yang dalam konteks ini dibatasi penafsirannya hanya oleh undang-undang atau aturan formal tertulis saja;
- faktor penegak hukum, yakni pihak yang diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum di masyarakat;
- faktor sarana dan prasarana, faktor ini sebagai pendukung para penegak hukum melaksanakan kewenangannya;
- faktor masyarakat, yakni dimana hukum berlaku. Budaya masyarakat yang abai mengenai hukum yang ada akan membawa pada sistem hukum yang berjalan tidak akan optimal, begitupula sebaliknya;
- faktor kebudayaan yang merupakan hasil karsa, rasa dan cipta masyarakat dalam bergaulan kehidupan bersama dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi peradaban suatu masyarakat akan semakin menunjukkan kualitas hukum yang berlaku ditengah-tengahnya.
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan, setidaknya melalui dua cara yakni tindakan dan pendidikan. Kesadaran hukum akan meningkat bilamana bentuk tindakan yang diambil berupa pemberatan terhadap acnacam sanksi yang akan diberikan dan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ditingkatkan oleh penegak hukum, serta yang dibutuhkan oleh masyarakat sebuah keteladanan akan tingkah laku yang semestinya diperbuat. (Mertokusumo, 2003, p. 128). Kemudian, peran pendidikan terutama mengenai pendidikan yang bermaterikan kewarganegaraan, advokasi kebijakan, yang membahas posisi penting keberadaan masyarakat, warga negara dan peran yang dapat dilakukannya dalam desain pembangunan hukum nasional.
Indikator kesadaran hukum masyarakat dapat dibentuk secara bertahap melalui hal-hal sebagai berikut (Puspa Yuliasari, Idrus Affandi, 2019, pp. 40–41):
- Pengetahuan hukum akan membawa seseorang untuk mengetahui akan aturan yang berlaku dan larangan serta sanksi yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran hukum. pengetahuan hukum menjadi bekal seseorang dalam memahami akan hukum yang ada dan berlaku dimasyarakat.
- Pemahaman hukum yang memuat infomasi mengenai ketentuan tertulis dan makna yang tersirat didalamnya, tujuan serta manfaat yang hendak dicapai dengan berlakunya ketentuan hukum yang berlaku.
- Sikap hukum atau legal attitude merupakan keterimaan atau ketidakterimaan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan perwujudan dari pemahaman seseorang akan ketentuan hukum, sehingga orang yang sepakat akan hukum yang berlaku akan mengapresiasi dan mendukung berjalannya aturan, begitupun sebaliknya.
- Pola perilaku hukum, hal ini menampilkan gambaran sejauh mana aturan yang berlaku di masyarakat dan kepatuhan terhadapnya. Sehingga kepatuhan yang tinggi dari masyarakat akan ketentuan yang berlaku menunjukkan nilai yang positif kesadaran hukum masyarakat.
Indikator atau parameter yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat sadar akan hukum pula dalam konteks negara modern dapat dilihat sebagai berikut (See, 2020, p. 47):
- Nilai-nilai demokrasi yang dianut dan dijunjung tinggi dalam semua sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegara.
- Dalam penyelenggaraan negara bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi merata pada semua wilayah negara.
- Kehidupan pers dan kebebasan dalam mengakses informasi dan mengemukakan pendapat.
- Angka kriminalitas rendah.
Masyarakat dalam kehidupan bernegara aktif dalam menyampaikan semua aspirasinya dalam berbagai bidang, diantaranya sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum dan bidang pemerintahan lainnya.
REFERENSI
Kenedi, J. (2015). Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Perguruan Tinggi Islam. Jurnal Madania, 19(2), 205–2016.
Mertokusumo, S. (2003). Bunga Rampai Ilmu Hukum. Liberty.
Puspa Yuliasari, Idrus Affandi, D. I. M. (2019). Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum Dalam Meningkatkan Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan. Jurnal Civicus, 19(2), 39–48.
See, B. R. (2020). Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia Yang Sadar Hukum. Caraka Justitita, 1(1), 42–50.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
Wiyono, S. (2016). Strategi Pengembangan Pendidikan Kesadaran Hukum Berdasarkan Pancasila. Maksigama Jurnal Hukum, 1 9(1), 1–20.